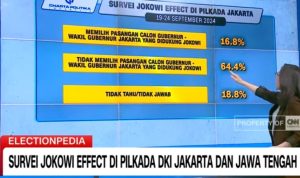Ichsanuddin Noorsy
Jakarta,Markaberita.id
Berbagai pendapat mengemuka ke ruang publik untuk merespon tampilnya pasangan Capres Anies-Cawapres Imin.
Tudingan dan penjelasan tentang hianat menghianati menghiasi pentas politik liberal. Kasus kardus durian yang sangat berpotensi menggeret Imin ke meja hijau korupsi ikut mewarnai heavy metal politik liberal itu.
Ada juga yang peduli pada nasib rakyat. Katanya, kasihan rakyat yang aspirasinya diombang-ambingkan elite politik.
Rasa iba ini disadari sebagai hilang etika dalam interaksi politik. Sirnanya etika itu seperti juga sikap Bank Dunia dalam menyahuti perang dagang AS-China. Pada 2015, menyaksikan China berhasil “menunggangi” ketentuan dagang WTO, Bank Dunia berpendapat, pentingnya etika beraksi. Keluhan mereka pada kemampuan China mengadopsi dan mengadaptasi teknologi komunikasi Barat.
Hanya dalam hitungan menit, China selalu dapat meniru produk baru korporasi AS. Maka Barat meradang dan menghadang. China pun menggalang serangan. Perang dagang berubah menjadi perang ekonomi dan teknologi.
Lahirlah perang dingin baru. Bersama mitra dagangnya, China mewujudkan perlawanan. Tudingan tentang lenyapnya etika dan pelanggaran hak asasi manusia dipandangnya dengan sebelah mata.
Kebebasan dagang, investasi dan keuangan yang dipropagandakan Barat dihentak China bersama mitra dagangnya. Isu etika pun lenyap. Siapa kuat, dia yang menang itulah kenyataan.
Dalam kebebasan politik dan perekonomian, isu etika memang ada di lingkungan agama. Isu etika hanya berlaku di antara rekan sejawat.
Terhadap lawan dan demi mencapai kemenangan, etika disimpan rapi dalam laci. Matinya 894 para KPPS dan pegiat pemilu 2019 adalah bukti, etika telah kehilangan makna. Maka politik liberal di manapun tak pernah utuh menghasilkan kerjasama sosial.
Political distrust mengalir menjadi sosial distrust dan bermuara pada ketimpangan sosial dan keterbelahan ras, agama, golongan dan suku. Di AS, JE Stiglitz menyebutnya sebagai ketimpangan rasial dalam level seperti kanker stadium empat.
Pada demokrasi liberal di Indonesia, ketimpangan dan keterbelahan itu mulai dirasakan sejak pemilu 2004.
Kini masyarakat terkotak-kotak dalam aliran, golongan sosial ekonomi dan ketokohan seseorang. Entah dipahami atau tidak, ketimpangan dan keterbelahan itu telah menjurus pada tergerusnya persatuan Indonesia.
Akar masalahnya terletak pada penghianatan berjamaah terhadap Sila ke empat dan Sila ke dua. Jika hilirnya pada ancaman atas persatuan Indonesia, maka seperti juga di AS, pasti hilirnya adalah sirnanya keadilan sosial. Ini berwujud pada rusaknya penegakan hukum, kokohnya ketimpangan pendapatan (melemahnya daya beli), dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Maka stabilitas politik dan stabilitas harga-harga menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Padahal, di negara manapun pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang pendayaagunaan kewenangannya guna mencapai dua kestabilan itu.
Jika suatu pemerintahan tidak peduli atas dua stabilitas tersebut, dan hanya peduli atas subyektivitas kepentingan kekuasaannya, maka hak kebebasan mengambil keputusan (discretionary policy) pasti akan mengenyampingkan mandatory policy, kebijakan-kebijakan yang dimanatkan konstitusi.
Begitulah kejinya kebebasan politik karena luka parahnya visi menjauhnya misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jangan mimpi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.
Kebebasan politik dan ekonomi memang tidak peduli dan bersandar pada keajegan hidup bersama yang menentramkan. Kehormatan dan penghargaan yang dicapainya selalu semu karena memang segalanya serba palsu. Untuk dan atas nama kebebasan itu, kekejian kata dan tindakan selalu menyertai. Inikah Negeri Pancasila?. (Red)